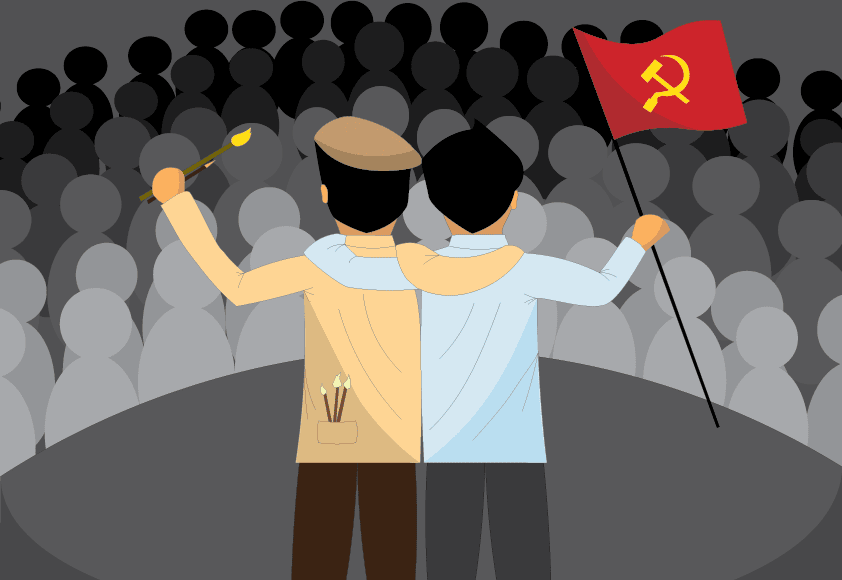Himmah Online – Pada 17 Agustus 1950 A.S. Dharta, M.S. Ashar, Henk Ngantung, Arjuna, Joebar Ajoeb, Sudharnoto, dan Njoto mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sebuah organisasi kebudayaan sayap kiri yang dibentuk untuk menghimpun para penulis, seniman, sastrawan, dan pekerja budaya lainnya. Ketujuh orang tersebut tergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).
Lekra hadir sebagai wujud kritik terhadap pandangan politisi dan seniman tua yang tergabung dalam Gelanggang Seniman Merdeka (GSM). Mereka menganggap bahwa revolusi telah gagal mengantarkan Indonesia menuju negara demokrasi.
Karena dinamika politik yang terjadi saat itu, banyak partai yang memiliki lembaga kebudayaan. Seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Partai Indonesia (Partindo) mempunyai Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI) dengan Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia (Laksmi), dan Nahdlatul Ulama pun turut membentuk Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi).
Sehingga, kesenian-kebudayaan menjadi syarat ajang tarung politik. Lantas lembaga kebudayaan pun dianggap sebagai jurus terjitu untuk menarik, menghimpun, dan mempengaruhi massa.
Awal Kantor Sekretariat dan Sanggar Lekra di Tjidurian 19
Njoto kala itu sedang berada di Surabaya. Di sana ia berkenalan dengan seorang pengurus surat kabar Sin Tit Po keturunan Tionghoa, Oey Han Djoen.
Oey kemudian pindah ke Semarang. Lalu pada 1958 Oey memboyong istri dan anaknya untuk pindah ke Jakarta lantaran ia terpilih sebagai wakil rakyat. Dengan selektif Oey memilih karakter rumah yang akan dihuninya. Jatuhlah ia pada rumah yang berdiri di Jalan Tjidurian, Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat.
Di Jakarta, Oey aktif di Lekra. Atas keinginannya sendiri, ia menjadikan rumahnya sebagai kantor sekretariat dan sanggar Lekra.
Saat rumah itu dijadikan kegiatan kesenian, Jane Luyke, istri Oey, sempat merasa kerepotan karena harus menyediakan makan dan minum untuk setiap tamu. Lama-kelamaan, Jane merasa kehilangan privasinya di rumah itu. Lalu Oey mengajak istri dan anaknya pindah ke Rawamangun, Jakarta Timur. Tjidurian 19 pun ditempati Lekra sepenuhnya.
Perjalanan Lekra
Mengutip mukadimah Lekra, bahwa mereka secara tegas berpihak pada rakjat dan mengabdi kepada rakdjat, adalah satu-satunya djalan bagi seniman-seniman, sardjana-sardjana, maupun pekerdja-pekerdja kebudajaan lainja untuk mentjapai hasil jang tahan oedji dan tahan waktu.
Garis berkesenian yang ditetapkan Lekra adalah kebudayaan yang mengacu pada rakyat. Dengan kata lain, seluruh seni budaya harus berpihak pada rakyat. Berkumandanglah seni rupa untuk rakyat, dengan realisme kerakyatan atau realisme sosialis (Dermawan 2000:48).
Istilah realisme sosialis ada setelah kongres pertama Persatuan Pengarang Uni Soviet pada 1934, walaupun diyakini istilah itu sudah ada sejak lama.
Terdapat dua aspek yang ditekankan pada realisme sosialis. Pertama, bahwa seni harus memperlihatkan realitas. Kedua, bahwa seni harus bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi yang sedang terjadi. Sehingga, ia dianggap bisa menciptakan keadaan yang lebih baik.
Lekra menggariskan gagasan realisme sosialis dalam konsep 1-5-1. Maksudnya, 1 artinya politik, politik yang merupakan panglima tindakan dalam seni. Lalu 5 yang artinya meluas dan meninggi; tinggi mutu ideologi dan mutu artistik; tradisi baik dan kekinian revolusioner; kreativitas individu dan kearifan massa; serta realisme sosial dan romantik revolusioner. Sedangkan 1 yang terakhir yaitu metode turun ke bawah (turba), artinya seniman harus turun ke masyarakat.
Karena memiliki paham yang sama, Lekra dan PKI pun menjadi dekat. Namun, bukan berarti Lekra dikuasai oleh PKI. Kedekatan ini menjadi simbiosis mutualisme. Lekra untung karena karya tulisan seniman-senimannya diterbitkan di surat kabar Harian Rakjat milik PKI. Begitu pun PKI yang mendapat dukungan Lekra dalam setiap acara kebudayaannya.
Lekra mengadakan konferensi nasional pertama pada 1959 di Surakarta dan dihadiri oleh Soekarno.
Bagi Lekra, seni tidak boleh hanya untuk seni, seni harus menghamba kepada politik yang sibuk berseni bebas, suka bereksperimen. Tidak ikut organisasi berarti berseberangan dengan revolusi. Berseberangan dengan revolusi berarti musuh rakyat.
Namun tak semua seniman di Tjidurian 19 memahami politik. Banyak seniman yang merasa keberatan dengan konsep 1-5-1 Lekra. Mereka kerap mendapat komentar dan didikte oleh partai. Banyak seniman yang bergabung dengan Lekra karena semata-mata untuk belajar, bergaul dengan seniman besar, mencari uang, dan Lekra punya fasilitas menyekolahkan ke luar negeri. Bahkan ada dari mereka yang tidak mengerti politik kiri-kanan.
Pertentangan Lekra versus Manikebu
Lekra semakin vokal pada 1962 terhadap mereka yang dianggap melawan gerakan rakyat. Kritikus sastra HB Jassin, misalnya, ia kerap dikritik oleh Lekra. Lekra pun jadi mendapat lawan pandang dalam kesenian.
HB Jassin, Taufiq Ismail, Goenawan Mohamad, Soe Hok Djin dan beberapa orang lain kemudian memprakarsai Manifes Kebudayaan (Manikebu). Kelompok yang tidak setuju bahwa seni harus terkotak dalam perspektif. Bagi mereka seni bersifat universal.
Wiratmo Soekito membuat naskah Manifes Kebudayaan yang rampung pada 17 Agustus 1963. Kemudian naskah tersebut diterima oleh Goenawan Mohamad dan Bokor Hutasuhut sebagai bahan yang diajukan dalam diskusi pada 23 Agustus 1963 di Jalan Raden Saleh, Nomor 19, Jakarta. Naskah tersebut diperbanyak dan disebarkan ke beberapa seniman sebagai landasan ideologi.
Sidang panitia pada 24 Agustus 1963 memutuskan bahwa Manifestasi Kebudayaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Manifes Kebudayaan, Penjelasan Manifes Kebudayaan, dan Literatur Pancasila. Kemudian hasil tersebut dipublikasi lewat surat kabar Berita Republik dalam rubrik Ruang “Forum” Sastra dan Budaya.
Beberapa bulan kemudian, Manikebu mendapat dukungan lebih dari seribu orang dari berbagai daerah.
Sebenarnya Manikebu sudah berbenturan sejak tahun 1950-an dengan Lekra lantaran mereka yang tergabung dalam GSM. Meskipun begitu, baik Lekra dan Manikebu memiliki pandangan yang sama bahwa seni harus mengabdi pada kepentingan masyarakat.
Tetapi, mereka memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Jika Lekra menitikberatkan pada realisme sosialis, sedangkan Manikebu berprinsip humanisme universal yang memiliki kebebasan dalam berekspresi.
Pada 1963-1965 PKI melakukan gerakan besar-besaran untuk memerahkan seniman, kaum muda, dan perempuan. Lekra didesak untuk menyatakan diri bahwa Lekra adalah PKI. Lekra menentang itu, sebab bagi mereka kegiatan kesenian tidak hanya semata untuk tujuan PKI. Hal itu melatarbelakangi konflik antara beberapa seniman Lekra dan PKI.
Lekra menjajaki puncak kejayaannya pada 1963. Mereka mengklaim memiliki 100.000 anggota dan 200 cabang organisasi.
Tahun 1964-1965 politik Lekra semakin kuat. Mereka ikut dalam demonstrasi untuk menentang perusahaan-perusahaan minyak asing dan gerakan politik lainnya.
Namun karena kedekatannya dengan PKI, Lekra terkena imbas dari peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Karya mereka dilarang beredar atau dihancurkan. Aktivisnya dihabisi dan diasingkan ke pulau terpencil. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang tidak pulang dari tempat pengucilan.
Akhir dari Lekra dan Tjidurian 19
Pertengahan Oktober 1965, Komando Distrik (Kodam) Militer Jakarta Timur menangkap Oey, pemilik rumah Tjidurian 19.
Pramoedya Ananta Toer, Henk Ngantung, dan seniman lainnya yang berafiliasi dengan Lekra juga ikut tertuduh terlibat dalam penyebaran paham komunis. Mereka menjadi tahanan politik di Pulau Buru selama belasan tahun tanpa proses peradilan.
Seiring dilarangnya PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya, Lekra pun akhirnya dibubarkan pada 1966 oleh rezim Orde Baru.
Tjidurian 19 pun turut terkena imbasnya, rumah tersebut mengalami perpidahan kepemilikan hingga fungsi bangunan.
Tjidurian 19 pernah diambil alih oleh Kodam Jaya dan dijadikan mess pasukan Angkatan Darat. Lalu rumah itu dijual kepada seorang pengusaha tanpa surat lengkap pada pertengahan 1990-an. Kemudian rumah tersebut dirobohkan dan dibangun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya yang masih bertahan hingga sekarang.
Tjidurian 19 menjadi hilang begitu saja dari ingatan masyarakat sebab propaganda politik yang membuat stigma bahwa Lekra merupakan salah satu lembaga yang ikut menyebarkan paham komunis.
Reporter: Himmah/Syahnanda Annisa
Editor: Pranoto