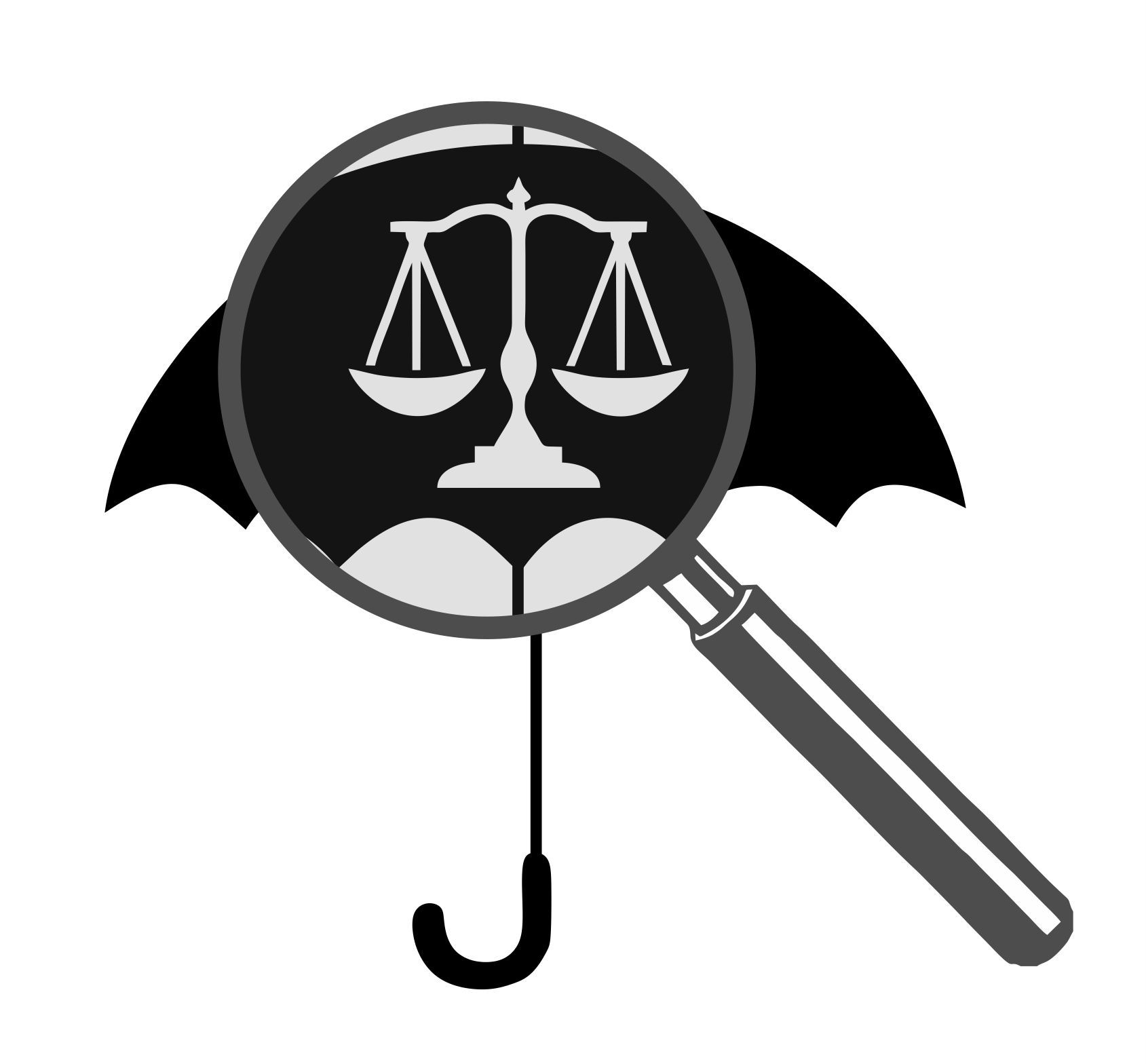Saat melakukan proses kerja jurnalistik, para pegiat pers mahasiswa (persma) acap kali dihadapkan pada posisi yang sulit. Di mana dewasa ini, banyak sekali terjadi kasus pembungkaman terhadap persma, misalnya intimidasi dari narasumber, pelarangan terbit, dan perampasan produk setelah terbit. Payung hukum terhadap persma pun menjadi perbincangan yang menarik saat ini. Sementara di lain sisi, dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak tertera nama persma di dalamnya. Lalu kemanakah persma harus berlindung?
Payung hukum terhadap persma amat lah penting. Hal tersebut sebagai pelindung jika terjadi masalah saat proses kerja jurnalistik berlangsung. Bahkan meskipun persma sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam melakukan proses kejurnalistikannya, selalu ada intimidasi dan pelarangan terbit.
Sebenarnya tidak hanya persma yang belum jelas payung hukumnya. Ada beberapa kasus yang menimpa jurnalis media massa dan sampai saat ini belum tuntas. Kasus Udin contohnya, sudah sangat lama sekali dan belum selesai hingga sekarang. Persoalan itu muncul karena negara belum bisa memberikan kepastian hukum secara penuh.
Walaupun sebenarnya, kebebasan pers sudah sangat dihargai. Kebebasan pers yang kita nikmati saat ini niscaya merupakan buah yang paling signifikan dari gerakan reformasi di Indonesia. Sudah selayaknya pers berterimakasih kepada kaum muda, mahasiswa dan rakyat, yang berjuang meruntuhkan kekuasaan rezim orde baru yang otoriter dan represif.
Berbagai kritik pun, terutama yang ditujukan ke alamat kekuasaan dengan mudah dapat disampaikan tanpa hambatan. Akses terhadap informasi pun mudah didapat, hampir tak adalagi fakta yang ditutup-tutupi seperti di masa orde baru. Lewat pers yang bebas ini, diharapkan proses demokratisasi dapat berkembang secara sehat.
Sepanjang sejarah Republik Indonesia, inilah kebebasan pers yang sebenar-benarnya. Kini, setiap warga negara dapat menerbitkan media tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah. Semarak kebebasan pers pun diwarnai dengan terbitnya berbagai macam media. Mutu penampilan, penyajian berita dan politik redaksionalnya pun sangat beragam.
Berkat dibukanya keran kebebasan pers pula, kini jumlah penerbitan pers berlipat-lipat dibanding tiras masa lalu. Apakah motivasi yang mendorong orang menerbitkan media? Inilah sebenarnya yang pertama kali harus dipertanyakan. Apakah para penerbit sudah benar-benar memahami misi pers? Agaknya sebagian besar penerbit memang memahaminya, meskipun ada beberapa di antaranya yang semata-mata terdorong oleh euphoria kebebasan pers. Bahkan ada pula yang semata-mata menginginkan keuntungan komersial.
Memang, posisi dan peran media sedikit banyak ditentukan oleh pemilik bersama pemimpin redaksi. Namun posisi pers di lingkup masyarakat sipil yang demokratis saat ini juga ditentukan oleh kepercayaan publik. Pers yang tak lagi dipercaya oleh publik dengan sendirinya akan ditinggalkan pembacanya. Sebab, publik yang cerdas menghendaki media massa yang mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan politik pemilik modal atau pribadi pemimpin redaksi.
Maka dari itu pers harus independen dari berbagai kepentingan politik, apalagi yang saling bertentangan. Agar pers mampu bersikap independen, dengan sendirinya pers harus mandiri secara ekonomi dan manajemen. Tetapi tetap, di atas segala-galanya adalah integritas. Hanya media pers dan juga wartawan yang berpegang teguh pada integritas moral yang tinggi lah, yang mampu independen. Dan jika pers dikelola secara profesional, suatu saat pers akan tumbuh sebagai industri penerbitan yang kuat secara ekonomi. Bahkan bukan tak mungkin kemudian tampil menjadi semacam konglomerasi yang sangat berkuasa dalam mempengaruhi opini.
Selain itu, ujung tombak media pers adalah wartawan. Mereka harus memiliki integritas moral yang tinggi sembari dipandu dengan Kode Etik Wartawan Indonesia yang berlaku untuk seluruh wartawan Indonesia, termasuk persma. Moral dalam arti kata yang luas ialah nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh dan berlaku di masyarakat beradab. Sedangkan integritas, sesungguhnya adalah “ideologi” bagi para pekerja pers, sebagai pegangan atau pedoman yang harus ditaati dalam menjalankan tugas profesi.
Seorang wartawan, selain harus profesional ia juga harus independen. Profesional dalam artian mampu bekerja dan menghasilkan karya sesuai ukuran-ukuran kelayakan jurnalisme, serta independen atau tak bergeming di tengah benturan berbagai kepentingan yang saling berbenturan. Namun keduanya saja tak cukup, wartawan harus pula mempunyai komitmen kuat dengan integritas moral yang teruji.
Jika semua itu dikaitkan dengan kebebasan pers, ada satu hal yang selama ini dilupakan. Bahkan juga oleh kalangan pers sendiri. Yaitu, kebebasan pers sesungguhnya bukanlah semata-mata kepentingan industri pers, pemilik modal, pemimpin redaksi, ataupun wartawan. Bukan! Kebebasan pers adalah hak publik, sebagai pengejawantahan dari hak asasi, sebagai konsekuensi logis dari hak yang bebas untuk mendapatkan akses informasi, sebagai salah satu akar tunjang demokrasi.
Kekuasaan pers semacam itu tidak seharusnya menjadi kekuasaan otokratis, melainkan kekuasaan yang menyadari tanggung jawabnya untuk mendidik dan mencerahkan publik. Seorang pemimpin redaksi bukan pula “diktatur intelektual”, melainkan seorang yang editorialnya berpihak pada kebenaran,keadilan, akal sehat, dan rakyat kecil yang tertindas.
Dengan demikian, maka media pers, begitu pula para pemilik modal, pemimpin redaksi, dan wartawan hanyalah sekedar sebagai pembawa amanat dari hak sipil publik tersebut. Supaya amanat tersebut dapat diemban sebaik-baiknya, maka syarat utamanya ialah: pekerja pers harus bersikap sebagai intelektual yang komitmen dengan profesi kewartawanan, dengan independensi yang teruji, dan dilandai integritas moral yang tinggi.
Hanya dengan sikap seperti itulah, pekerja pers mampu membantu proses pertumbuhan masyarakat sipil yang cerdas, yang mampu menilai dengan akal sehat, yang demokratis dan dinamis. Itulah yang disebut pekerja pers yang memiliki integritas moral yang tinggi. Justru karena memiliki integritas itu pulalah, pers mendapat semacam “hak istimewa” yang secara konstitusional diakui oleh undang-undang yang menjamin kebebasan pers.
Memang, meskipun tak banyak, ada beberapa di antaranya yang merasa “bebas” dalam mengelola media, sehingga pers dianggap bukan lagi sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan umum. Bisa dibilang, bebas yang “kebablasan”. Anehnya, selama ini tak jelas apa yang dimaksud dengan “pers yang kebablasan”. Apa kriteria atau parameternya?
Jika yang dimaksud ialah “kebablasan” dalam mengkritik kekuasaan, tentulah tudingan itu salah alamat. Namun, jika yang dimaksud ialah “pers kuning” yang beritanya insinuatif dan bombastis, sesungguhnya di mana pun dan kapan pun gaya pers semacam itu selalu ada. “Pers kuning” atau “koran kuning” tentu tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai perkembangan pers. Apalagi jika tudingan itu tidak berdasarkan data yang akurat. Meskipun tanpa data, kalaupun ada pers yang dianggap “kebablasan” –apapun parameter atau kriterianya–pasti jumlahnya tidaklah banyak.
Apalagi jika berujung pada pembungkaman. Ketika ada pembredelan, sebenarnya yang harus rugi bukan jurnalis, tetapi masyarakat karena informasi terhambat. Apalagi secara berangsur-angsur publik mulai menyadari hak-hak sipil mereka, antara lain hak untuk mendapatkan akses informasi, hak untuk mengemukakan pikiran,berekspresi, dan berkumpul secara bebas.
Oleh karena itu, semua media, termasuk persma harus bisa membangun kepercayaan publik dengan menyajikan liputan-liputan yang berkualitas. Termasuk persma yang tak jarang mendapatkan intimidasi. Setiap persma harus melakukan proses kerja jurnalistik sesuai kode etik jurnalistik. Lakukan pula secara profesional, jika ragu-ragu tanyakan. Jika terdapat ancaman baik fisik maupun psikis, adukan ke Dewan Pers.
Kendati tidak diterangkan dalam UU nomor 40 tadi, persma pun sebenarnya masih tetap dilindungi oleh undang-undang yang sama dalam hal keterbukaan informasi publik. Juga oleh UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyasar pada kebebasan mimbar akademik.
Persma sendiri lahir dari kampus dan digerakan oleh aktivis kampus, namun kehadirannya belum diperlakukan sama dengan media massa pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa syarat yang mesti dipenuhi, standar perusahaan misalnya, lalu konsistensi penerbitan apakah setiap hari atau tidak, serta bagaimana kompetensi wartawannya.
Jadi penulis kira, menempatkan persma sejajar dengan pers umum merupakan salah satu upaya menempatkan persma agar lebih serius dalam mengelola media. Sehingga persma nantinya mampu mengusung isu yang berbeda dan menjadi bacaan alternatif dari ruang kampus, yang tentu saja akan berbeda dengan pers umum. Persma memiliki peranan penting dalam menentukan dan mengawal arah kebebasan pers bangsa ini ke depan, sebagai media dan wahana berlatih sebelum memasuki dunia pers umum yang semakin ketat dan tantangan yang beraneka ragam. (Aji Setiawan- Alumnus Universitas Islam Indonesia (UII), mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia-Reformasi Korda Dista Yogyakarta 1999-2002)