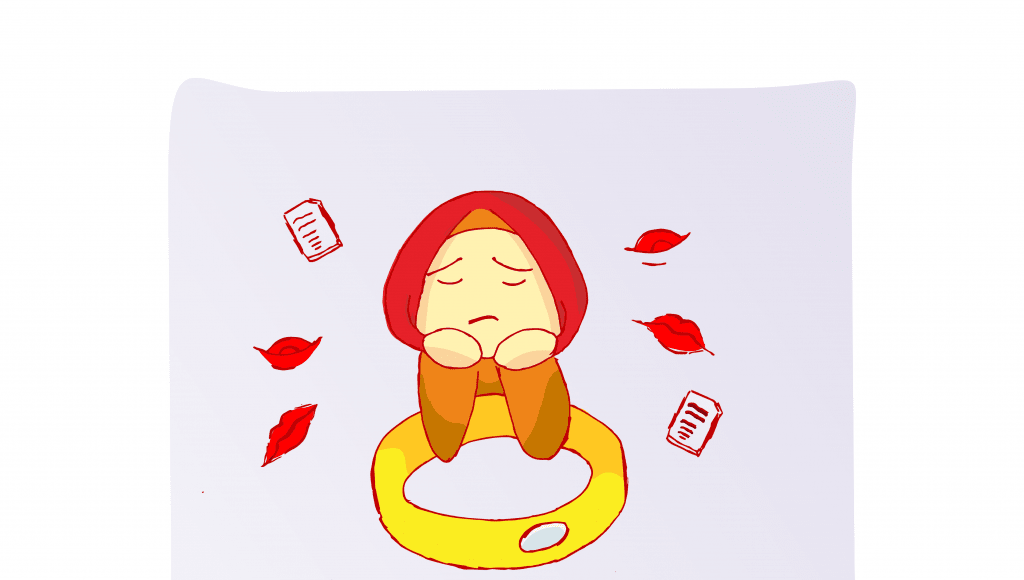Kenapa makin ke sini rasanya waktu berjalan makin cepat saja. Rasanya aku baru bangun pukul sebelas lewat tepat saat adzan dzuhur berkumandang, lalu tiba-tiba saat ini sudah pukul sembilan malam kala kebanyakan lampu-lampu di rumah penduduk dimatikan.
Rasanya baru kemarin aku menapaki Jogja dan menikmati segala keramahannya, tapi tiba-tiba malam ini aku sadar bahwa sudah empat tahun atau mungkin lebih aku menjadi salah satu penduduk Jogja, meskipun bukan penduduk tetap.
Terkadang aku kembali ke kotaku untuk menunaikan kewajiban menjawab pertanyaan-pertanyaan keluargaku salah satunya ialah “Kapan pulang?” Meskipun kenyataannya pertanyaan itu jarang disampaikan, tapi setiap kali pertanyaan itu datang berarti memang aku harus benar-benar pulang.
Menjawab pertanyaan tersebut tidaklah sulit. Aku tinggal meminta uang tambahan untuk membeli tiket bus dan menjawab “Besok, mau bersih-bersih dulu,” atau pun jawaban-jawaban lain yang sekiranya dapat menenangkan hati keluargaku. Mengingat aku belum merdeka secara finansial jadi mau tidak mau ada banyak pertanyaan dimana aku harus memberi jawaban yang memuaskan.
Meski begitu, tetap ada beberapa pertanyaan yang jawabannya tidak begitu memuaskan, bahkan ada pula yang benar-benar tidak dapat aku jawab. Pertanyaannya memang tidak sesulit ujian masuk perguruan tinggi atau CPNS seperti kata orang, tetapi menjawabnya bisa jadi lebih sulit dari itu semua.
Usiaku sekarang sudah menginjak kepala dua, tepatnya dua puluh dua tahun. Bagi orang Indonesia usia tersebut bisa dikatakan matang buat perempuan. Pada usia tersebut, aku tidak lagi dianggap sebagai remaja apalagi anak-anak. Sudah banyak hal yang bisa aku lakukan daripada sebelumnya.
Untuk mencari pekerjaan tidak ada lagi ketakutan tidak diterima karena faktor usia pada masa ini, meskipun kualifikasinya bukan hanya soal usia saja. Aku tidak terlalu takut ditanyai tentang pekerjaan oleh keluargaku, karena sudah sejak aku berada di semester awal bangku perguruan tinggi aku sudah mulai ikut bekerja dengan keluargaku.
Pekerjaan apapun aku lakukan, mulai dari menjaga toko, keluar kota untuk proyek, dan berjualan kecil-kecilan juga pernah aku lakukan. Meskipun upahnya tidak sebesar jika seseorang bekerja sungguhan, tetapi upah dari hasil kerjaku sudah mampu memuaskan nafsuku untuk membeli beberapa hal yang aku mau tanpa harus merengek meminta uang.
Karena percayalah meskipun aku tidak lagi remaja atau anak-anak, saat aku meminta uang untuk membeli camilan, nilainya tidak lebih dari sepuluh ribu rupiah.
Pertanyaan perihal kelulusan pun tidak terlalu aku pusingkan. Aku selalu memiliki banyak alasan yang bisa aku jadikan sebagai jawaban. Keluargaku tahu aku sempat mengalami beberapa kendala saat awal-awal memasuki bangku kuliah, mereka paham bahwa hal itu juga mungkin berdampak pada proses pendidikanku.
Mungkin aku bisa menjawab bahwa aku sedang mengikuti proyek kampus dan aku harus menunda skripsiku, karena jika aku lulus terlalu cepat bisa jadi peluangku untuk mengikuti proyek tersebut pun musnah. Apalagi jika yang aku jadikan alasan-alasan adalah proyek yang memiliki keuntungan besar. Namun, bukan semua pertanyaan itu yang aku sulit untuk menjawabnya.
Melainkan pertanyaan “Kapan nikah?”.
Jika pertanyaan itu dari teman, aku masih bisa menganggapnya sebagai candaan, toh teman-temanku itu juga belum menikah pada saat menanyakan hal itu. Tetapi berbeda hal saat yang bertanya adalah keluargaku sendiri.
Ketakutan akan ditanyai “Kapan nikah?” Akan dua kali berlipat ganda saat keluargaku yang bertanya. Sebenarnya aku takut bukan karena tidak laku, tetapi justru latar belakang keluargaku sendiri yang mengakibatkan ketakutan itu.
Singkat cerita, aku berasal dari keluarga yang kata orang broken home. Bapak dan ibuku sudah cerai sejak aku berada di bangku sekolah dasar. Sebenarnya aku tidak tau betul alasan perceraian itu. Sejak dari perpisahan bapak dan ibuku aku lebih sering tinggal sendiri di kontrakan sementara dua adikku tinggal bersama nenek.
Bapakku lebih sering bekerja, jadi jarang pulang ke rumah dan ibuku tinggal di kota lain. Bisa dibilang aku memang tidak terlalu dekat dengan orang tuaku, pada saat perceraian mereka pun sejujurnya aku tidak merasa sedih, malahan aku lebih cenderung senang ketika hal itu terjadi.
Alasannya karena aku tidak akan mendengar keributan-keributan mereka lagi. Tentu saja keributan antar orang tua akan sangat berpengaruh kepada psikologis anak, terutama saat anak juga terlibat dalam keributan ini.
Sejujurnya aku tidak takut kalau aku tidak laku. Jika mau, aku bisa saja sudah menikah sekarang dengan lelaki yang aku kehendaki. Tetapi ada alasan lain yang lebih mendasar untuk menunda sementara pernikahan itu.
Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk individu. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda dengan individu lainnya, baik secara fisik bahkan secara emosi. Setiap individu tentu juga memiliki idealisme dan egoisme yang berbeda.
Pernikahan adalah sebuah upaya formal untuk menyatukan dua individu baik yang sama-sama karena cinta atau hanya karena pernikahan benar-benar untuk formalitas sebagai manusia saja. Penyatuan individu pastilah tidak mudah.
Kedua individu tersebut harus benar-benar beradaptasi dengan baik supaya dalam menjalankan kehidupan bersama yang harmonis. Jika keduanya tidak dapat beradaptasi, pasti akan sering terjadi adu pendapat yang bisa jadi berujung dengan pertengkaran.
Bagiku sendiri beradaptasi dengan orang baru tidaklah mudah. Belakangan aku lebih nyaman menjalani kehidupan dengan diriku sendiri daripada harus berbaur dengan orang lain. Saat aku bersama dengan orang lain dan terjadi ketidakcocokan pendapat, memang tidak sering terjadi percekcokan, tetapi hal itu menimbulkan kegelisahan dari hatiku karena aku lebih sering untuk memilih mengalah.
Aku lebih sering mengikuti apa yang orang lain inginkan karena aku takut apa yang aku inginkan nantinya tidak memuaskan hati mereka dan menimbulkan sinis terhadap diriku. Tindakanku tersebut semata-mata untuk menciptakan kenyamanan untuk diriku sendiri, namun berangsur-angsur yang terjadi bukanlah demikian. Jadi, daripada harus terlibat dalam argumen yang berbeda aku lebih memilih untuk sendirian.
Dari beberapa latar belakang itu, ketakutan untuk menikah bukan hanya yang berdampak untuk kenyamananku saja, namun juga ketakutan jika suatu saat akan berdampak pada anak-anakku kelak. Aku pernah ditanya tentang apa cita-citaku, dan jawabanku akan selalu sama yaitu ingin menjadi seorang ibu yang baik.
Hal itu bukanlah omong kosong dan bagiku bukan juga cita-cita yang biasa, karena orang-orang yang memiliki latar belakang hampir serupa denganku ternyata juga memiliki ketakutan yang sama dalam hal pernikahan dan menjadi orang tua.
Mereka takut kegagalan juga akan terjadi kepada mereka. Ketakutan akan memberi pola asuh yang buruk terhadap keturunan mereka. Karena adanya kegagalan pada masa lalu mempengaruhi psikologi, dimana unsur ini menjadi perilaku bawah sadar yang akan terus terbawa sepanjang hidup.
Jadi, ketika keluargaku menanyakan “Kapan nikah?”
Jawabku “Next question, please.”